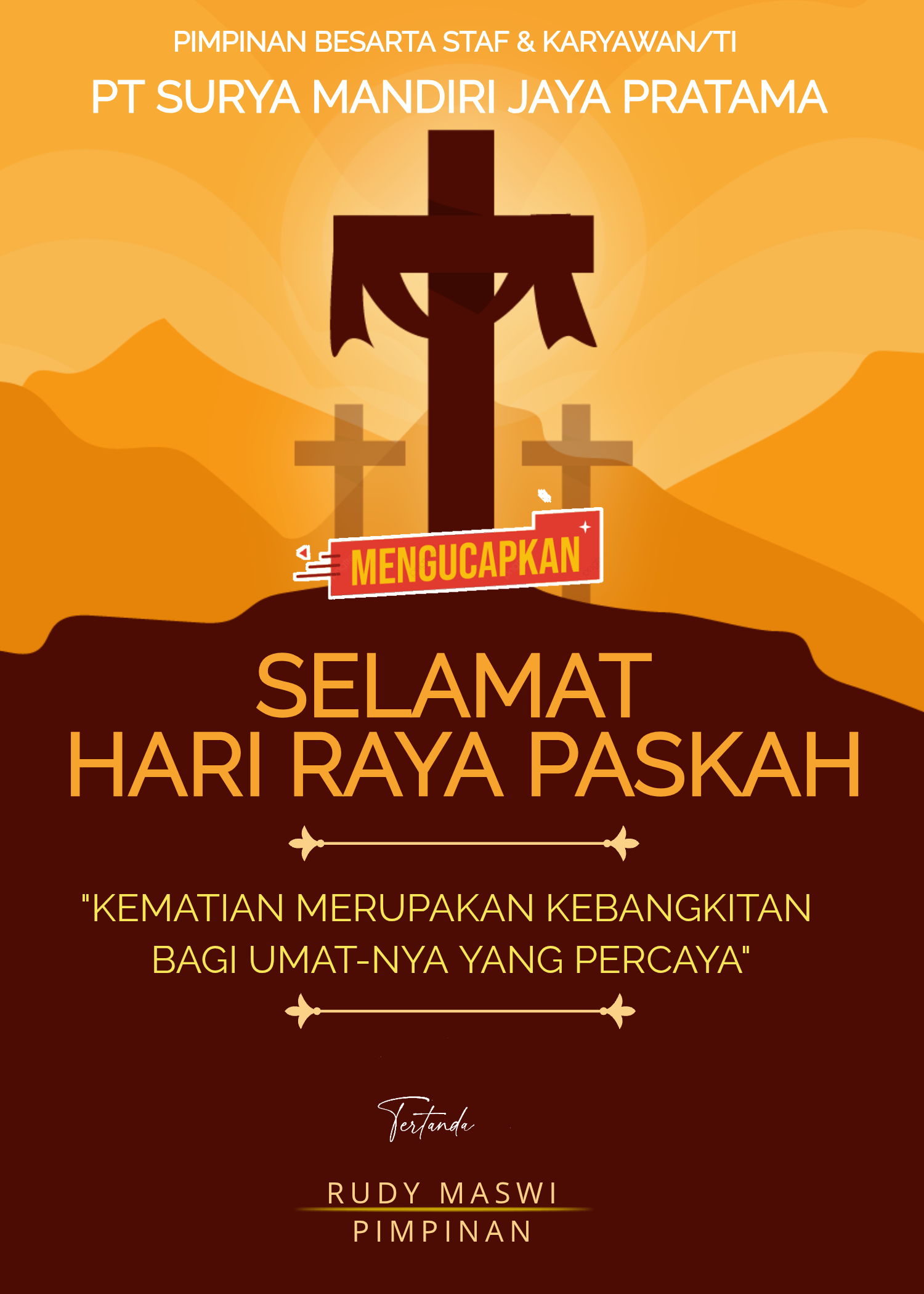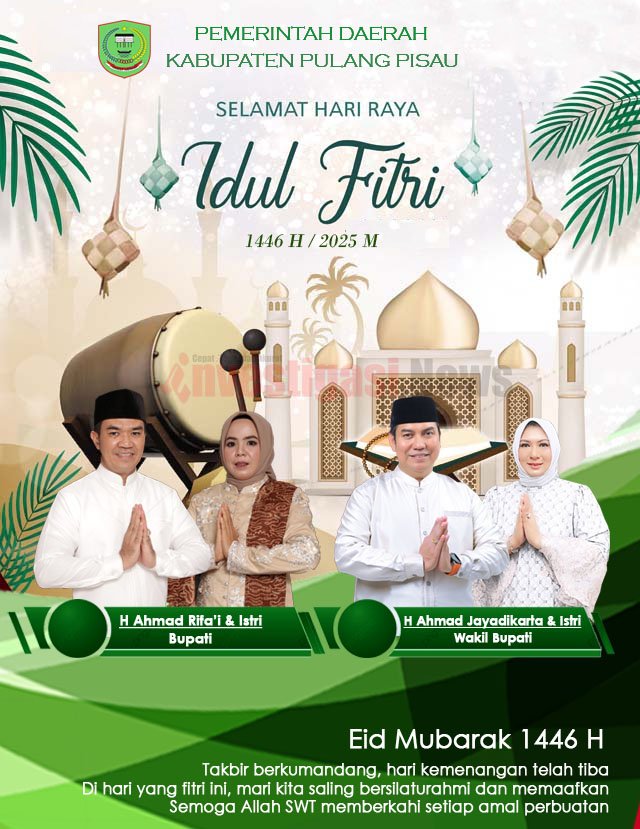Dulu, kesepian mungkin diasosiasikan dengan lansia yang hidup sendiri, atau mereka yang jauh dari pusat keramaian. Tapi hari ini, di tengah dunia yang hiper-terhubung secara digital, kesepian justru menjangkiti banyak anak muda. Kita menyaksikan paradoks besar: dunia semakin terhubung lewat internet, tetapi manusia justru merasa makin terasing.
Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat ironi ini dengan jelas. Di warung kopi, anak muda duduk berdekatan, tetapi tenggelam dalam layar masing-masing. Dalam keluarga, percakapan kian singkat, tergantikan notifikasi dan emoji. Di media sosial, kita punya ratusan teman, tetapi tak punya satu pun yang benar-benar bisa diajak bicara ketika hati sedang sesak.
Data dari Cigna International Health (2021) mencatat bahwa 62% generasi milenial dan Gen Z merasa kesepian secara kronis, meskipun mereka adalah pengguna teknologi paling aktif. Di Indonesia sendiri, survei Jakpat (2023) menunjukkan bahwa 57% anak muda usia 18–30 tahun mengaku sering merasa “sendiri dalam keramaian digital”.
Hasil survei Kementerian Kominfo dan UNICEF (2022) menunjukkan bahwa hanya 35% pelajar Indonesia yang memiliki literasi digital dalam kategori baik. Sementara itu, 75% pelajar lebih banyak mengakses media hiburan dibandingkan konten edukatif atau budaya lokal. Di Maluku Utara sendiri, data BPS (2023) mencatat bahwa dari total pengguna internet usia 15–24 tahun, lebih dari 70% menggunakan internet untuk hiburan, dan kurang dari 20% untuk kegiatan literasi atau pembelajaran.
Fenomena ini menarik untuk dibaca melalui kacamata sosiologi, khususnya pemikiran Émile Durkheim tentang anomie, yaitu kondisi ketika individu mengalami keterputusan dari nilai-nilai sosial yang mengikat mereka secara kolektif. Dunia digital yang serba cepat telah menggeser relasi sosial yang bersifat hangat dan langsung menjadi relasi transaksional dan visual. Orang merasa ada di tengah banyak orang, tapi tidak merasa “dimiliki” oleh siapa pun.
Erving Goffman, dalam teori dramaturgi-nya mengungkapkan bahwa manusia membagi hidupnya dalam dua panggung: panggung depan (apa yang diperlihatkan ke publik) dan panggung belakang (dunia batin yang disembunyikan). Media sosial menjadi panggung depan yang paling ramai: tempat kita pamer tawa, pencapaian, dan kebahagiaan. Tetapi panggung belakang kita ruang sunyi yang sebenarnya semakin sempit dan dingin.
Kesepian sosial ini tidak hanya berdampak pada kesehatan mental, tapi juga melemahkan solidaritas sosial. Di banyak tempat, termasuk di Kabupaten Kepulauan Sula, gejala ini mulai terlihat. Generasi muda makin jarang ikut arisan keluarga, kumpulan adat, atau duduk bercerita bersama tetua kampung. Sebuah studi kecil yang saya lakukan di Sanana pada awal 2024 menunjukkan bahwa 7 dari 10 pemuda di Sanana lebih akrab dengan teman daring daripada tetangga sebelah rumah.
Ini tentu bukan hanya soal teknologi, tapi tentang pergeseran nilai. Ketika ruang digital menjadi rumah utama, rumah sosial yang sebenarnya menjadi kosong. Ketika percakapan dikemas dalam bentuk cepat dan lucu, perasaan mendalam menjadi asing dan melelahkan.
Lantas apa yang bisa kita lakukan?
Pertama, kita harus menghidupkan kembali ruang sosial yang autentik. Ruang berkumpul entah di rumah, masjid, komunitas pemuda, atau balai desa perlu diisi dengan obrolan yang bermakna, bukan hanya formalitas. Kedua, pendidikan dan kampanye publik harus mulai menyentuh isu literasi emosi dan relasi, bukan sekadar literasi digital. Anak-anak muda perlu diajarkan cara mendengar, merasakan, dan berbagi tanpa takut terlihat lemah.
Era digital bukan kutukan, tapi tantangan. Dan di tengah tantangan ini, semestinya kita tidak lupa menjadi manusia: makhluk sosial yang haus akan kehadiran nyata, bukan sekadar sinyal Wi-Fi yang kuat.
Penulis: Akademisi STAI Babussalam Sula Maluku Utara