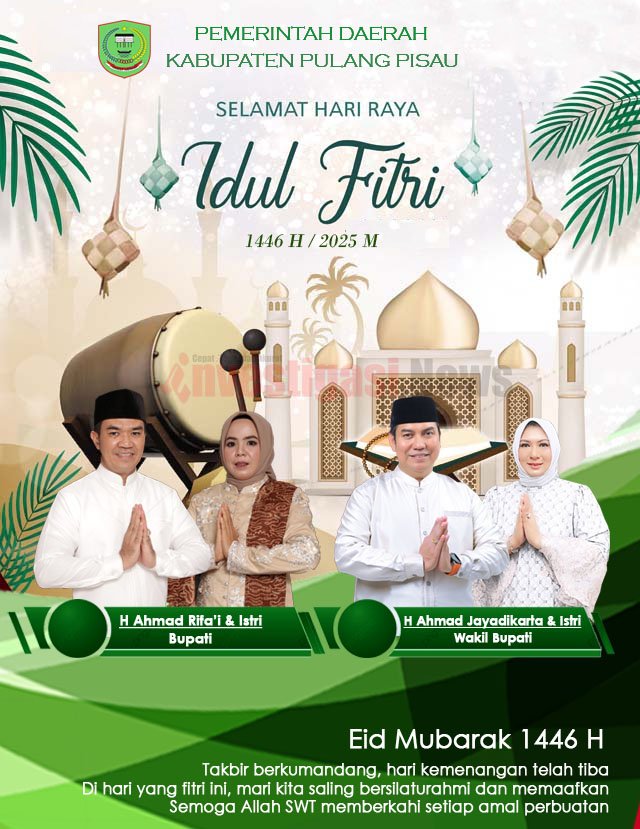Malut, investigasi.news-, Persoalan sampah telah menjadi masalah klasik yang terus berulang hampir di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Kota Sanana, Ibu Kota Kabupaten Kepulauan Sula. Tumpukan sampah yang menggunung di pinggir jalan, lorong-lorong kota, hingga permukiman warga, menjadi pemandangan yang lazim dan terus berulang dari waktu ke waktu.
Jika ditelusuri, alasan yang sering dikemukakan pemerintah daerah selalu sama: keterbatasan armada angkut, kurangnya tenaga kerja kebersihan, dan minimnya anggaran pengelolaan sampah. Padahal, akar dari masalah ini bukan hanya soal anggaran dan fasilitas, melainkan ”soal pola pikir atau mindset” dalam memandang sampah.
Saat ini, sebagian besar sistem pengelolaan sampah masih berbasis pada pendekatan “angkut dan buang”, sampah dikumpulkan dari rumah warga lalu dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Padahal, pendekatan ini justru memperparah masalah. TPA cepat penuh, biaya operasional terus membengkak, dan lingkungan pun makin tercemar.
Namun sejatinya, ”solusi ada dan bisa dilaksanakan dengan sederhana”, asalkan dilakukan dengan pendekatan yang holistik dan melibatkan semua pihak.
*Edaran KLHK Jadi Momentum Perubahan*
Merespons kondisi nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pada 7 Februari 2025 menerbitkan edaran penting yang menegaskan bahwa pengelolaan sampah tidak boleh lagi hanya bergantung pada TPA. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota ”diwajibkan mengelola sampah dari sumbernya (hulu)”, yaitu dari rumah, RT, RW, desa, dan kelurahan dan hanya residu akhir yang boleh dibuang ke TPA.
Artinya, pemerintah daerah harus mulai membangun sistem pengelolaan sampah yang terdesentralisasi, berbasis masyarakat, dan didukung oleh lintas sektor.
*Model Solusi: TPS Pemusnahan Sampah Berbasis Desa*
Model pengelolaan ini bisa dimulai dari skala terkecil, yaitu desa atau kelurahan di setiap wilayah, pemerintah dapat membentuk Kelompok Kerja Pengelola Sampah yang terdiri dari 10-15 orang. Tugas kelompok ini meliputi:
– Mengedukasi warga agar memilah sampah dari rumah
– Mengambil sampah secara terjadwal dari tiap RT
– Mengolah sampah secara langsung di TPS (Terminal Pemusnahan Sampah) tingkat desa
Berbeda dengan TPS konvensional yang menjadi tempat menumpuk sampah, TPS berbasis desa ini justru menjadi pusat pengelolaan dan pemusnahan sampah secara tepat guna, ramah lingkungan, dan tidak mencemari udara, tanah, maupun air.
*Teknis Pengelolaan: Mudah, Murah, dan Ramah Lingkungan*
Sampah yang terkumpul diklasifikasikan menjadi empat kategori besar:
1. Sampah Organik (±50%)
– Diolah menjadi kompos atau media tanam
– Bisa juga diubah menjadi karbon padat (arang) menggunakan teknologi sederhana
– Kompos ini dapat dijual dan mendukung tren urban farming
2. Sampah Anorganik Ekonomis (±20%)
– Seperti plastik, botol, dan kemasan bersih
– Dipilah dan dijual ke industri daur ulang atau diolah menggunakan mesin pres/pencacah skala UMKM
3. Sampah Logam dan Barang Bekas Elektronik
– Kaleng, besi tua, dan sisa alat rumah tangga
– Dijual ke pengepul logam dengan nilai ekonomi yang baik
4. Residu Sampah Tak Berguna (±30%)
– Dimusnahkan menggunakan teknologi non-polutif seperti insinerator mini atau sistem pirolisis sederhana
*Potensi Ekonomi: Dari Sampah Jadi Penghasilan*
Dengan estimasi pengelolaan 2 ton sampah per hari di satu desa, berikut simulasi potensi pendapatan per bulan:
| Jenis Sampah | Volume/Bulan | Harga Rata-rata | Estimasi Pendapatan |
|—————————–|————–|——————|———————–|
| Kompos kering/media tanam | 7.500 kg | Rp2.500/kg | Rp18.750.000 |
| Sampah plastik | 10.000 kg | Rp1.200/kg | Rp12.000.000 |
| Logam dan barang bekas | 150 kg | Rp5.000/kg | Rp750.000 |
| *Total Pendapatan* | — | — | *Rp31.500.000* |
Jika sistem ini dikelola oleh 15 orang, maka setiap orang berpotensi memperoleh penghasilan sekitar *Rp2.100.000 per bulan*. Ini membuka peluang bagi *Dinas Tenaga Kerja* untuk menciptakan *100–200 lapangan kerja langsung* hanya dari pengelolaan sampah di Kota Sanana.
*Peluang Urban Farming: Kompos Jadi Produk Unggulan*
Tren urban farming kini berkembang pesat, termasuk di kota besar seperti Ternate. Kompos kering yang dihasilkan desa dapat dijual sebagai media tanam dengan harga bersaing. Di Ternate, media tanam ukuran 25 kg dijual Rp100.000. Jika desa hanya menjual Rp50.000, maka produknya akan sangat kompetitif.
Dinas Pertanian bisa mengambil bagian penting untuk melakukan:
– Standarisasi produk kompos
– Pelatihan dan pendampingan kelompok desa
– Promosi dan distribusi produk ke luar daerah
*Sinergi Antar Dinas: Kunci Sukses Sistem Ini*
Sistem pengelolaan sampah ini tidak bisa dijalankan oleh satu SKPD saja, dibutuhkan peran aktif dan koordinasi lintas sektor:
– DLH (Dinas Lingkungan Hidup): Edukasi masyarakat, pengawasan operasional, penyediaan sarana daur ulang dasar.
– Disperindagkop: Fasilitasi alat pres plastik dan mesin pencacah untuk mendukung UMKM berbasis sampah.
– Dinas Tenaga Kerja: Pelatihan dan perekrutan tenaga kerja lokal berbasis desa.
– Dinas Pemuda dan Olahraga: Menggerakkan pemuda desa untuk terlibat dalam kegiatan produktif dan inovatif.
– Dinas Pertanian: Pendampingan kompos, integrasi dengan program ketahanan pangan.
– BPMD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa): Sebagai pembina Pemerintah Desa dan para Kepala Desa, BPMD memiliki peran penting dalam mendorong para kepala desa untuk mengambil inisiatif dan kepemilikan dalam program ini melalui Musrenbang Desa dan alokasi dana desa.
*Catatan Penting:*
Seluruh SKPD yang terlibat justru bisa memanfaatkan sumber daya dan anggaran sektoral masing-masing** untuk mendukung pengelolaan sampah berbasis desa ini. Tidak perlu lagi menumpuk beban di DLH atau menunggu anggaran tambahan, karena program ini bisa diintegrasikan ke dalam kegiatan rutin tahunan tiap SKPD.
*Kesimpulan: Sampah Adalah Aset, Bukan Beban*
Sudah waktunya Kota Sanana mengambil langkah nyata dalam membangun sistem pengelolaan sampah berbasis desa yang efektif, mandiri, dan produktif. Sistem ini tidak hanya menyelesaikan persoalan lingkungan, tapi juga membuka lapangan kerja baru, menghasilkan produk bernilai jual, dan menghemat anggaran daerah secara signifikan.
Jika dijalankan secara kolaboratif, maka sampah tidak lagi menjadi sumber masalah, melainkan sumber berkah bagi masyarakat.
Oleh: Abdurahman Kaka Duwila
(Pemerhati lingkungan).