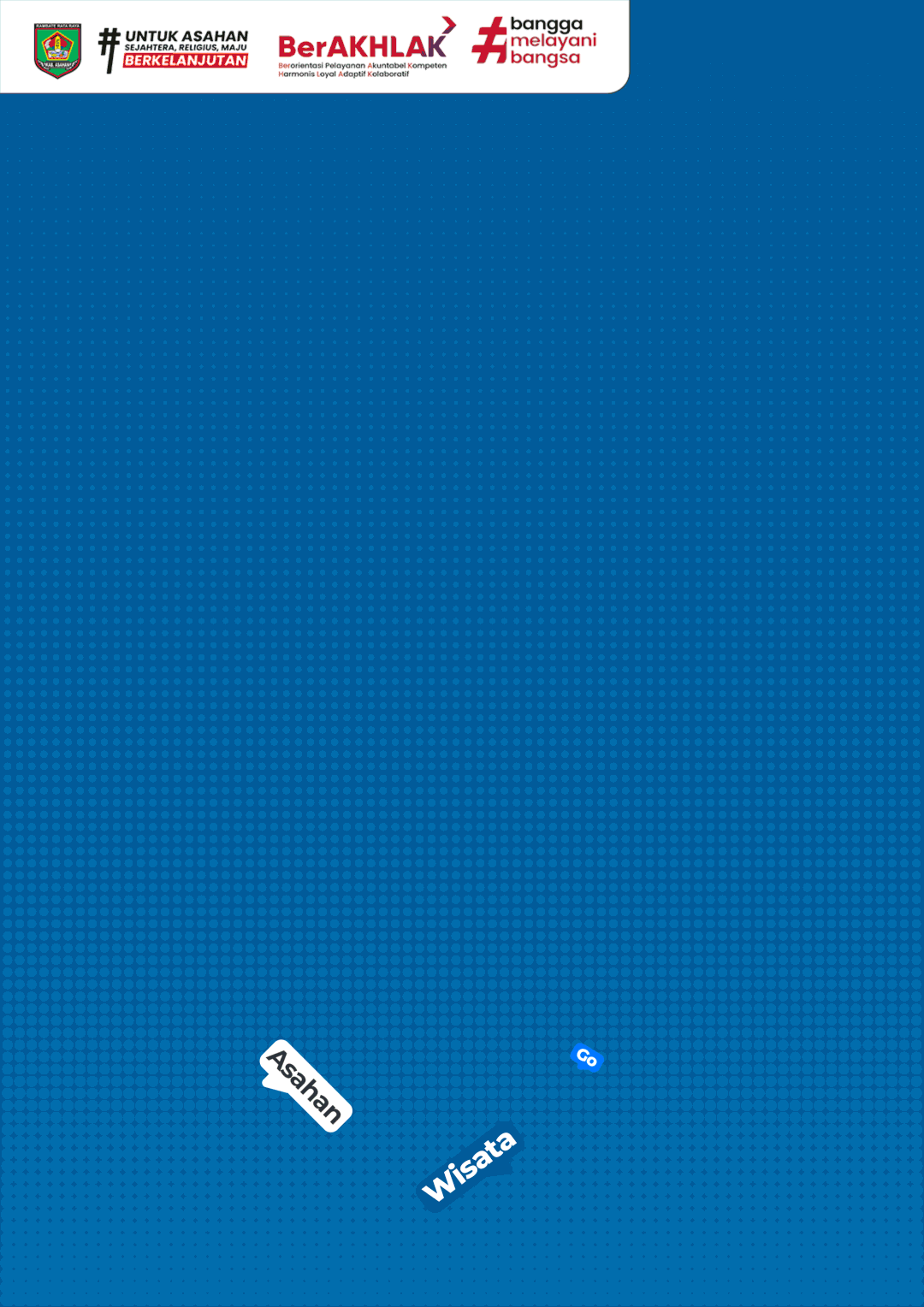Setelah libur panjang, para santri Pondok Pesantren Alquran Darul Inqilabi Lubuk Basung kembali memulai tahun ajaran 2024/2025 pada Juli 2024. Minggu pertama di asrama menjadi masa adaptasi bagi santri, terutama bagi mereka yang baru pertama kali tinggal jauh dari orang tua. Tak sedikit yang menangis, rindu rumah, dan berharap segera dijemput kembali.
Bagi santri laki-laki, setelah satu minggu adaptasi, mereka diajak bermain futsal bersama beberapa ustaz di lapangan. Kegiatan ini bertujuan untuk mencairkan suasana dan mengurangi rasa rindu kampung halaman. Rata-rata santri menunjukkan antusiasme tinggi, termasuk Muhammad Ismail, santri kelas III yang sebelumnya tidak terlalu tertarik bermain futsal.
Meski awalnya tidak begitu menyukai futsal, semangat teman-teman dan suasana yang menyenangkan membuat Ismail ikut tergerak. Ia menyadari bahwa banyak santri sudah membawa sepatu futsal dari rumah. Sementara dirinya belum memilikinya, hal ini membuat Ismail merasa sedikit tertinggal.
Cerita pun semakin mengharukan ketika Ismail dengan tulus bertanya kepada ayahnya, “Ayah, ada uang?” Ketika sang ayah bertanya untuk apa, Ismail menjawab, “Kalau Ayah ada uang, saya rencana mau pinjam untuk beli sepatu futsal.” Ayahnya bertanya lagi, “Kapan?” dan Ismail menjawab, “Nanti saya kabarkan kapan saya mau beli sepatu.”
Meski sang ayah adalah pimpinan pondok, Ismail berusaha keras untuk tidak memanfaatkan posisinya. Ia tidak ingin mendapat perlakuan khusus. Ia ingin diperlakukan sama seperti santri lainnya, membuktikan bahwa dirinya bisa mandiri dan berjuang seperti teman-temannya.
Setiap hari, saya datang ke pondok sekitar pukul 04.00 WIB untuk mendampingi santri di musala. Di sanalah saya sering melihat Ismail berbincang dengan Dodi dan Habib, para pembina asrama. Saya merasakan ada sesuatu yang dipendam Ismail, sesuatu yang belum sempat ia utarakan.
Hingga suatu malam setelah salat Magrib, Ismail memohon berbicara dengan saya. Setelah salat Isya, ia menyampaikan keinginannya untuk mencari uang tambahan saat libur pondok, seperti hari Minggu. Saya terharu sekaligus terkejut. “Ayah punya uang. Kalau Ismail minta, ayah beri,” kata saya. Namun Ismail menjawab dengan penuh tekad, “Saya ingin mandiri, Ayah. Saya tidak mau menyusahkan Ayah. Minggu kemarin saya bantu Tante Opet membersihkan ladang jagung. Uangnya saya pakai untuk beli sepatu futsal. Saya tidak mau menyusahkan Ayah.”
Ismail menambahkan dengan suara penuh syukur, “Saya ingin bermain bola, tapi sepatu saya tidak ada. Sekarang saya sudah punya sepatu futsal. Terima kasih, Ayah, yang selalu sayang sama Ismail. Kalau ada kerja hari Minggu, ajak Ismail, ya. Ismail ingin mandiri, seperti yang Ayah ajarkan.”
Mendengar kata-katanya, saya merasa begitu tersentuh. Saya tidak melarang Ismail bekerja, tapi saya khawatir, jika ia kesulitan, ia akan memilih diam. Dengan senyum bangga, saya memeluknya dan berkata, “Terima kasih, Ismail, atas usahamu. Ayah bangga dengan semangatmu untuk mandiri.”
Dalam pelukan itu, Ismail berbisik pelan, “Makasih, Ayah.” Momen itu bukan sekadar kisah anak dan ayah, tetapi juga pelajaran berharga tentang kemandirian, keadilan, dan rasa syukur. Ismail telah menunjukkan bahwa cita-cita dan kebutuhan bisa diraih dengan kerja keras, tanpa harus mengandalkan posisi atau privilese.
Oleh: Hasneril, SE