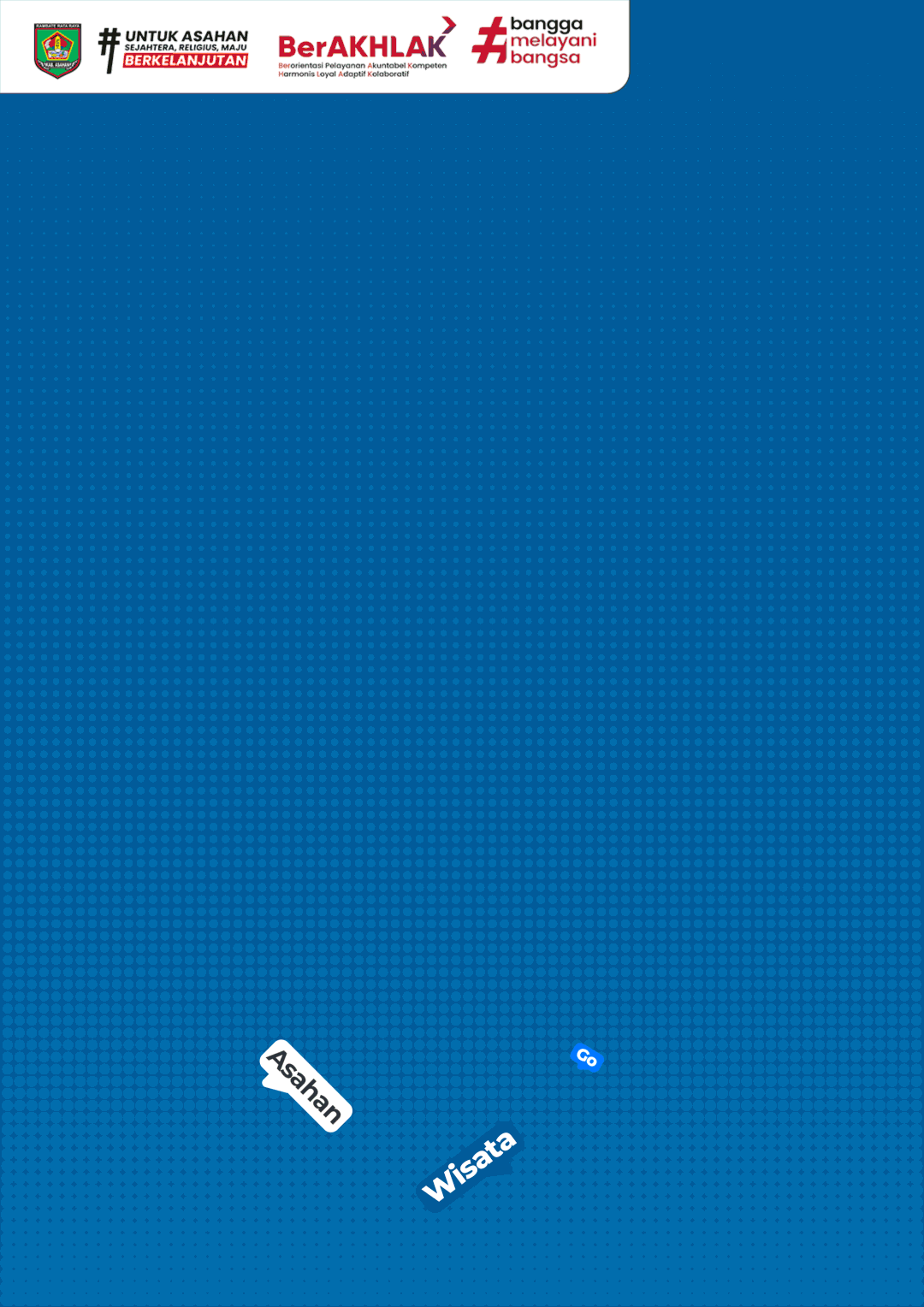NTT | Investigasi.News — Kematian seorang siswa Sekolah Dasar (SD) berusia 10 tahun di Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang diduga mengakhiri hidupnya setelah menghadapi tekanan terkait kebutuhan alat tulis sekolah, telah memicu pertanyaan serius: di mana negara ketika seorang anak terdesak oleh kemiskinan hingga kehilangan harapan hidup?
Peristiwa ini bukan sekadar tragedi kemanusiaan. Ia membuka dugaan kegagalan berlapis dalam sistem perlindungan sosial, pendidikan dasar, dan pendampingan anak rentan—terutama di wilayah yang selama ini kerap berada di pinggiran kebijakan.
Gubernur Nusa Tenggara Timur, Melki Laka Lena, dalam pernyataan terbukanya, secara eksplisit mengaitkan tragedi ini dengan kelemahan sistem pemerintahan. “Saya menyampaikan duka cita sedalam-dalamnya atas meninggalnya adik kita di Jerebuu. Ini menjadi refleksi kegagalan sistem, dari pemerintah provinsi, Kabupaten Ngada, hingga pemerintahan paling bawah,” ujar Melki.
Pernyataan ini penting secara politik dan administratif. Kegagalan sistem disebut secara terbuka oleh pejabat setingkat gubernur—bukan sebagai retorika, melainkan sebagai “pengakuan” adanya masalah struktural. Namun, pernyataan tersebut juga memunculkan pertanyaan lanjutan: kegagalan sistem yang mana, dan siapa yang harus bertanggung jawab.
Berdasarkan penelusuran redaksi, korban berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi sangat terbatas. Korban tinggal bersama neneknya, sementara sang ibu—orang tua tunggal—harus menghidupi lima anak dengan bekerja sebagai petani dan buruh serabutan.
Sejumlah sumber menyebutkan adanya dugaan surat yang ditinggalkan korban sebelum meninggal dunia, yang menggambarkan tekanan psikologis berat terkait kebutuhan sekolah. Dengan kata lain, informasi ini menunjukkan adanya sinyal tekanan mental serius pada anak usia 10 tahun.
Jika dugaan tersebut terbukti, maka peristiwa ini tidak dapat direduksi sebagai masalah keluarga atau tragedi individual. Ia menjadi indikator kegagalan negara menjangkau kemiskinan ekstrem di level paling dasar: “rumah tangga, sekolah, dan desa”.
Respons pemerintah pusat muncul dalam bentuk empati. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut kasus ini sebagai “atensi bersama” dan menekankan pentingnya penguatan data kemiskinan. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menyebutnya sebagai “cambuk” bagi semua pihak.
Namun dalam perspektif kebijakan publik, pernyataan tersebut justru membuka persoalan mendasar: Jika data kemiskinan masih perlu diperkuat, berapa banyak anak lain yang saat ini hidup di luar jangkauan sistem negara?
Kemiskinan ekstrem, terutama pada anak, bukan peristiwa tiba-tiba. Ia merupakan akumulasi dari kegagalan deteksi dini, lemahnya pendampingan, dan absennya intervensi tepat waktu.
Dalam kerangka hukum nasional, alat tulis bukanlah bantuan sukarela. Ia adalah bagian dari hak dasar pendidikan. Landasan hukumnya jelas:
1. Pasal 31 ayat (2) UUD 1945;
2. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Ketika seorang anak diduga merasa tertekan karena tidak mampu membeli alat tulis seharga Rp10.000, maka yang patut dipertanyakan bukan empati publik, melainkan fungsi negara dalam memastikan hak pendidikan dasar benar-benar hadir di lapangan.
Berdasarkan investigasi lapangan, ada setidaknya empat lapisan kelemahan struktural yang perlu diuji secara terbuka oleh negara:
1. Pendataan kemiskinan ekstrem: Apakah keluarga korban terdaftar sebagai penerima bantuan sosial? Jika terdaftar, mengapa kebutuhan paling dasar masih tidak terpenuhi? Jika tidak terdaftar, siapa yang gagal melakukan verifikasi?
2. Sekolah sebagai benteng pertama perlindungan anak: Apakah pihak sekolah mengetahui kondisi sosial korban? Jika mengetahui, mengapa tidak ada intervensi? Jika tidak mengetahui, bagaimana sistem deteksi dini dijalankan?
3. Pendampingan sosial di tingkat desa: Program bantuan sosial mensyaratkan kehadiran pendamping. Ketidakhadiran negara di level desa menunjukkan persoalan implementasi, bukan sekadar anggaran.
4. Absennya layanan psikososial anak rentan: Dugaan tekanan mental pada anak usia 10 tahun menunjukkan ketiadaan sistem pendampingan psikologis bagi anak dalam kondisi krisis.
Keempat aspek ini tidak berdiri sendiri. Mereka adalah mata rantai yang saling terhubung—dan ketika satu putus, dampaknya bisa fatal.
Dalam etika kebijakan publik, anak adalah subjek yang wajib dilindungi tanpa syarat. Tragedi ini memperlihatkan bahaya ketika kebijakan sosial direduksi menjadi laporan, angka, dan seremonial, sementara realitas di lapangan luput dari perhatian.
Pernyataan Gubernur NTT membuka pintu penting menuju akuntabilitas. Namun pintu ini akan kehilangan makna jika tidak diikuti langkah nyata. Negara perlu, setidaknya:
1. Melakukan audit terbuka atas pendataan dan distribusi bantuan sosial;
2. Mengklarifikasi peran sekolah dan dinas pendidikan;
3. Menilai tanggung jawab administratif pihak terkait;
4. Membangun sistem pencegahan yang aktif, bukan reaktif.
Tragedi ini menuntut pertanggungjawaban nyata, bukan sekadar simpati. Ketika tekanan ekonomi sederhana merenggut nyawa seorang anak, yang diuji bukan hanya efektivitas program sosial, melainkan kehadiran negara bagi warganya yang paling rentan—apakah hadir sebelum semuanya terlambat.
Negara tidak selalu gagal karena niat jahat. Ia kerap gagal karena pembiaran, rutinitas, dan absennya rasa urgensi.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih menunggu pernyataan resmi dari pihak kepolisian terkait hasil penyelidikan, serta konfirmasi dari pihak sekolah dan dinas terkait di Kabupaten Ngada mengenai pendampingan dan bantuan yang diterima keluarga korban. Setiap pihak yang disebut memiliki hak jawab sesuai UU Pers.
Severinus T. Laga