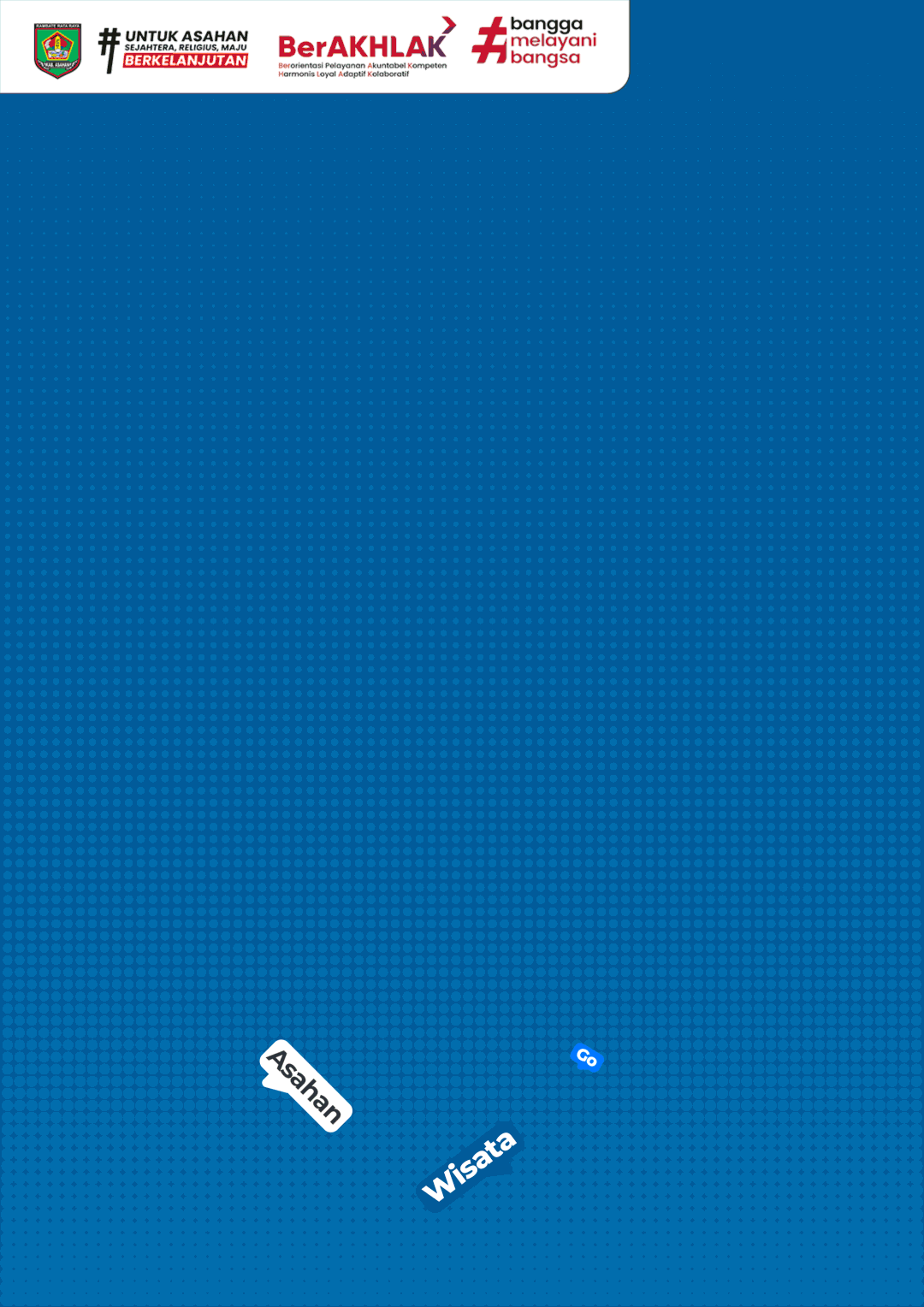NTT | Investigasi.News — Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) kembali menjadi momentum reflektif atas kondisi kemerdekaan pers di Indonesia yang secara normatif dijamin konstitusi, namun dalam praktik kerap menghadapi tekanan struktural, kriminalisasi, dan intervensi kekuasaan.
Dalam peringatan Hari Pers Nasional 2026, Advokat Rikha Permatasari menegaskan bahwa pers bukan sekadar institusi penyampai informasi, melainkan pilar keempat demokrasi yang memiliki fungsi konstitusional sebagai pengawas kekuasaan (watchdog) dan penjaga akal sehat publik.
“Pers adalah suara nurani bangsa. Ketika mekanisme kontrol negara melemah atau disalahgunakan, pers yang merdeka, beretika, dan berintegritas menjadi benteng terakhir kebenaran,” tegas Rikha dalam pernyataan resminya.
Secara hukum, kemerdekaan pers dijamin Pasal 28F UUD 1945 dan ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Namun Rikha menilai, jaminan normatif tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam praktik penegakan hukum.
Dalam beberapa tahun terakhir, ia menyoroti maraknya penggunaan instrumen hukum pidana maupun perdata untuk menekan kerja jurnalistik, termasuk pelaporan wartawan dengan pasal-pasal karet, intimidasi hukum, hingga upaya pembungkaman informasi yang berkepentingan publik. “Ketika karya jurnalistik dipidana tanpa melalui mekanisme hak jawab dan hak koreksi sebagaimana diatur UU Pers, itu bukan penegakan hukum, melainkan bentuk pelemahan demokrasi,” ujarnya.
Meski demikian, Rikha menegaskan bahwa kemerdekaan pers tidak boleh dipahami sebagai kebebasan absolut tanpa batas. Ia menekankan pentingnya Kode Etik Jurnalistik (KEJ) sebagai rambu moral dan profesional yang membedakan kerja pers dengan propaganda, opini pesanan, atau disinformasi.
Menurutnya, jurnalisme yang berintegritas adalah jurnalisme yang:
1. Berbasis verifikasi fakta,
2. Berimbang dan tidak menghakimi,
3. Menghormati asas praduga tak bersalah,
4. Berpihak pada kepentingan publik, bukan kepentingan kekuasaan.
“Pers yang beretika justru semakin kuat secara hukum, karena bekerja dalam koridor kebenaran dan kepentingan umum,” kata Rikha. Ia menilai jurnalisme investigatif memiliki peran strategis dalam membuka fakta-fakta yang kerap luput dari pengawasan formal negara, mulai dari dugaan penyalahgunaan wewenang, korupsi, manipulasi data publik, hingga pelanggaran hak asasi manusia.
Dalam banyak kasus, ungkapnya, produk jurnalistik justru menjadi pintu masuk koreksi kebijakan dan penegakan hukum, bukan sebaliknya. “Sejarah menunjukkan, banyak kasus besar terungkap bukan karena keberanian kekuasaan, tetapi karena keberanian pers,” tegasnya.
Rikha mengingatkan bahwa membungkam pers sama dengan membungkam hak publik untuk tahu. Dalam perspektif hukum dan demokrasi, tindakan tersebut merupakan ancaman serius terhadap negara hukum (rechtsstaat) dan prinsip akuntabilitas.
Ia menyerukan agar seluruh pemangku kepentingan—aparat penegak hukum, pejabat publik, dan elite kekuasaan—menghormati kemerdekaan pers sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem demokrasi. “Pers harus tetap menjadi cahaya di tengah gelapnya disinformasi, mata dan telinga rakyat, serta pengingat bahwa kebenaran tidak boleh ditundukkan oleh kekuasaan,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, ia menegaskan bahwa masa depan demokrasi Indonesia sangat ditentukan oleh keberanian pers menjaga integritas dan independensinya. “Pers yang kuat melahirkan demokrasi yang bermartabat. Pers yang merdeka memastikan keadilan tetap hidup. Ketika pers dibungkam, sesungguhnya yang sedang dilumpuhkan adalah hak rakyat untuk mengetahui kebenaran,” pungkasnya.
Severinus T. Laga