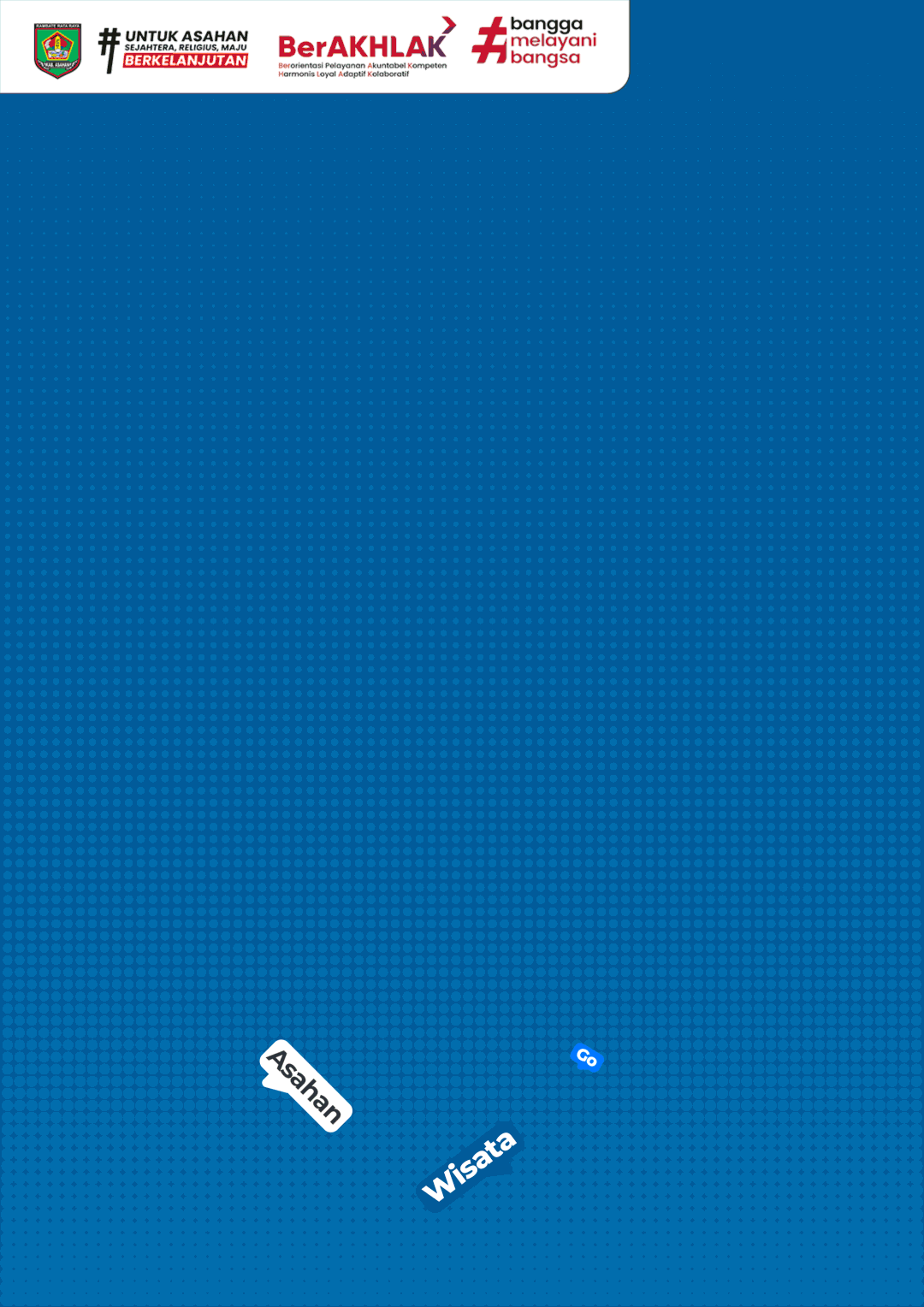NTT, Investigasi.News — Perdebatan mengenai arah kebijakan pendidikan nasional kembali menguat seiring wacana implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara nasional. Di tengah euforia program penanganan stunting dan peningkatan kehadiran siswa, kritik tajam datang dari Politisi dan Pemerhati Global, Leopold Therik.
Program MBG sendiri diklaim pemerintah sebagai bagian dari strategi penanganan stunting, peningkatan kualitas gizi anak, serta penguatan partisipasi sekolah. “Pertanyaannya bukan soal niat baik. MBG lahir dari niat yang baik. Tetapi kebijakan publik tidak bisa berhenti pada niat. Ia harus menjawab akar persoalan,” ujar Leopold.
Ia mempertanyakan prioritas fiskal negara: apakah pemerintah sedang menyelamatkan masa depan anak bangsa, atau sekadar menenangkan statistik jangka pendek?
Akar Masalah Pendidikan: Lebih dari Sekadar Perut Kosong
Leopold menilai problem pendidikan Indonesia bersifat struktural dan tidak bisa direduksi pada isu gizi semata. Ia merinci persoalan mendasar yang selama ini belum tertangani secara serius: ketimpangan akses, mutu guru yang rendah, kurikulum yang tidak kontekstual, infrastruktur sekolah rusak, serta biaya pendidikan tersembunyi yang membebani keluarga miskin.
Data Badan Pusat Statistik (BPS), menurutnya, menunjukkan fenomena learning poverty yang mengkhawatirkan: anak-anak hadir di sekolah, tetapi tidak mencapai kompetensi literasi dan numerasi yang memadai. “Anak Indonesia banyak yang sekolah, tetapi tidak benar-benar belajar. Ini krisis kognitif, bukan sekadar krisis kalori,” tegasnya.
Di sejumlah daerah, terutama kawasan timur Indonesia, faktor putus sekolah bukan hanya karena kekurangan gizi, melainkan biaya seragam, buku, transportasi, hingga pungutan tidak resmi.
Anggaran Ratusan Triliun: Dampak Struktural atau Populer Sesaat?
Program MBG diperkirakan membutuhkan anggaran ratusan triliun rupiah jika diterapkan secara nasional. Leopold mempertanyakan rasionalitas fiskal kebijakan tersebut di tengah masih banyaknya persoalan mendasar pendidikan. “Setiap rupiah anggaran negara harus diuji dampak jangka panjangnya. Apakah ini investasi struktural atau sekadar kebijakan populer?” katanya.
Ia menyoroti kondisi guru honorer yang masih hidup dalam ketidakpastian, pemangkasan anggaran pelatihan guru, serta belum optimalnya link and match pendidikan vokasi dengan dunia kerja.
Menurutnya, apabila anggaran sebesar itu dialihkan untuk pendidikan gratis total—termasuk buku, seragam, transportasi, akses internet, rehabilitasi sekolah, serta peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru—dampaknya dinilai lebih berkelanjutan.
Risiko Ketergantungan dan Politisasi
Di luar aspek fiskal, Leopold juga mengingatkan potensi dampak sosial-budaya MBG. Ia menilai program yang terpusat dan masif berisiko menciptakan ketergantungan serta membuka ruang politisasi anggaran. Sehingga program ini memerlukan mekanisme pengawasan ketat.
Ia mengutip pemikiran Paulo Freire tentang pendidikan sebagai proses pembebasan manusia. “Pendidikan tidak boleh direduksi menjadi alat distribusi bantuan. Jika anak datang ke sekolah hanya karena makan, maka fungsi pembebasan itu hilang,” ujarnya.
Risikonya, apabila insentif makan menjadi satu-satunya daya tarik sekolah, maka fungsi pendidikan sebagai ruang pembebasan dan pengembangan daya pikir dapat tereduksi.
Meski demikian, pemenuhan gizi tetap merupakan prasyarat penting bagi kesiapan belajar. Namun dalam konteks budaya komunal Indonesia, ia menilai intervensi pangan seharusnya berbasis keluarga dan ekonomi lokal, bukan sentralisasi dapur negara yang rawan penyimpangan apabila tanpa tata kelola transparan.
Belajar dari Negara Lain
Leopold membandingkan kebijakan pendidikan di sejumlah negara yang dinilainya berhasil membangun kualitas sumber daya manusia melalui reformasi pendidikan mendasar.
Ia mencontohkan Finlandia, Korea Selatan, dan Vietnam sebagai negara yang memprioritaskan pendidikan gratis dan berkualitas, peningkatan martabat profesi guru, serta disiplin fiskal dalam sektor pendidikan. “Jaminan makan tetap ada, tetapi bukan sebagai panglima kebijakan. Yang menjadi inti adalah sistem pendidikan yang kuat,” katanya.
Rekomendasi Kebijakan
Sebagai solusi, Leopold mengusulkan pendekatan yang tidak bersifat biner, namun menempatkan prioritas secara tegas:
1. Pendidikan gratis total tanpa pungutan, termasuk buku, seragam, transportasi, dan akses internet.
2. MBG terbatas dan kontekstual, difokuskan pada daerah rawan stunting, dikelola koperasi lokal dan BUMDes.
3. Revolusi kualitas guru, melalui peningkatan gaji, seleksi ketat, dan pelatihan berkelanjutan.
4. Audit fiskal terbuka, agar anggaran pendidikan tidak menjadi komoditas politik.
5. Desentralisasi kebijakan pendidikan, memberi ruang bagi daerah menentukan prioritas sesuai kebutuhan lokal.
Masa Depan atau Popularitas?
Leopold menegaskan, bonus demografi Indonesia hanya akan menjadi berkah apabila negara berani mengambil kebijakan jangka panjang yang mungkin tidak populer. “MBG mungkin membuat anak kenyang hari ini. Pendidikan gratis dan bermutu akan membuat mereka berdaulat seumur hidup,” ujarnya.
Perdebatan ini pada akhirnya bukan soal memilih makan atau belajar, melainkan bagaimana negara merancang kebijakan yang tidak terjebak pada solusi jangka pendek.
Pada akhirnya, sejarah tidak mencatat seberapa populer sebuah program, melainkan seberapa dalam ia mengubah kualitas generasi. Yang diuji bukan hanya niat baik pemerintah, melainkan keberanian merancang kebijakan yang melampaui satu periode kekuasaan.
Ia menutup pernyataannya dengan satu pesan tegas: MBG akan membuat anak kenyang hari ini. Pendidikan gratis dan bermutu akan membuat mereka berdaulat seumur hidup.
Severinus T. Laga